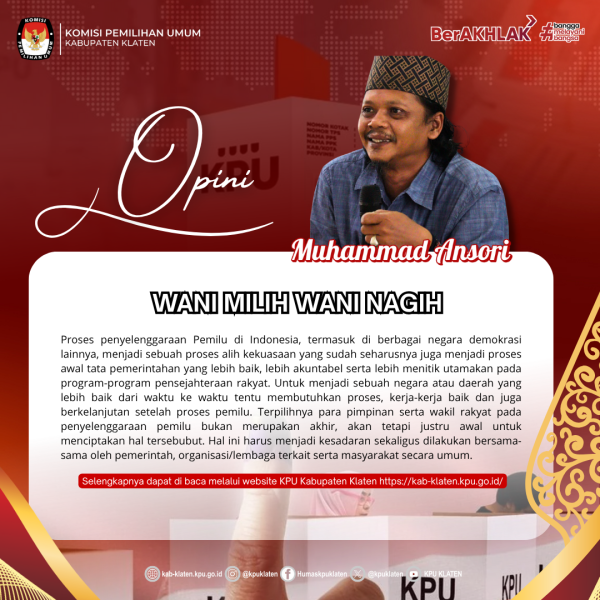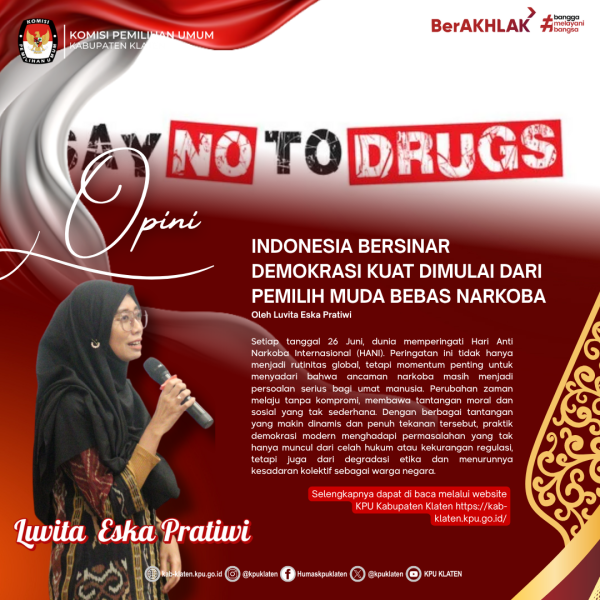OBAH NGAREP KOBET MBURI
Oleh: Muhammad Ansori Obah Ngarep Kobet Mburi merupakan salah satu falsafah Jawa yang secara harfiah bisa dimaknai bahwa “Setiap gerakan pemimpin di depan akan membawa pengaruh pada rakyat yang dipimpinnya”. Falsafah atau pepatah ini akan selalu benar dan relevan dalam setiap kontek kepemimpinan dari masa ke masa. Apapun tindakan apalagi kebijakan yang diambil oleh pemimpin akan berdampak pada sebagian dari hidup dan kehidupan rakyatnya. Dalam proses menentukan pemimpin harus disertai kesadaran bahwa sebagian dari keputusan dalam kehidupan masyarakat -bahkan dalam hal pribadi, nantinya akan diserahkan kepada pemimpin terpilih. Untuk itu, dalam proses menentukan dan memilih pemimpin harus disertai pengetahuan, kesadaran sampai pada keyakinan yang cukup sebelum akhirnya menentukan dan memilih pemimpin. Sebaliknya, seorang calon pemimpin harus menyadari bahwa keputusannya tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada yang dipimpinnya sehingga harus dilakukan dengan cerdas, bijaksana dan mempertimbangkan dari berbagai faktor. Jika dalam memilih pemimpin dilakukan sembarangan dengan pertimbangan sesaat karena uang, wajah, obral janji maupun hal-hal bersifat sesaat lainnya, maka jika ketika pemimpin telah terpilih terpilih tidak seperti yang diinginkan maka rakyat tidak boleh kecewa dengan keputusannya. Sebaliknya, calon pemimpin juga harus benar-benar didasari dengan kesadaran bahwa selama memimpin, segala tindakan dan keputusannya akan berdampak langsung maupun tidak langsung pada masyarakat yang dipimpinnya. Tindakan, kebijakan sampai pada keputusan sembarangan, tidak amanah, atau tidak bertanggung jawab, maka rakyat atau bawahannya yang akan menanggung akibatnya. Pada teori ini maka secara otomatis harus berlaku hukum timbal balik, yaitu masyarakat menentukan pemimpinnya harus dengan niat, pengetahuan, maupun kesadaran yang baik. Demikian sebaliknya bahwa seorang calon pemimpin juga harus disertai niat, visi, misi, program, tindakan serta keteladanan yang baik pula. Jika dua kutub ini bisa bertemu maka sangat mungkin dalam perjalanan pemerintahan akan lebih mudah, baik dan berdampak baik pula. Lebih dari itu, keputusan para pemimpin yang baik, cerdas, dan bijaksana akan membawa kesejahteraan maupun kebahagiaan bagi rakyat yang dipimpinnya. Dalam konteks kepemiluan, mengenali calon pemimpin bisa dilakukan jauh hari sebelum tahapan pemilu dimulai. Bahkan sangat dimungkinkan masyarakat bisa mengajukan calon pemimpin yang menurut masyarakat baik dan bisa dipercaya untuk memimpinnya. Hal ini bisa dilakukan tentu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku misalnya seperti harus melalui partai politik atau gabungan partai politik atau bisa juga melalui jalur perseorangan. Hal ini secara lebih rinci sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Diantara contoh kebijakan pemimpin yang berdampak langsung pada kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya, antara lain: kebijakan tentang harga BBM, program bantuan sosial, kebijakan harga bahan makanan pokok, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Dalam kontek yang lebih luas, kebijakan tentang kerjasama dengan luar negeri terkait perdagangan, ekspor / impor, pertanian maupun sektor lain yang bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat akan membawa dampak langsung kepada masyarakat pula. Selain cerdas dan visioner untuk kebaikan rakyat yang dipimpinnya, seorang pemimpin juga harus bijaksana dalam membuat kebijakan atau keputusan dengan mempertimbangan efek baik dan buruknya dari segala bidang. Contoh kebijakan pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan untuk memperlancar arus ekonomi juga harus disertai dengan pertimbangan dampak kerusakan alam dan lingkungan yang bisa ditimbulkan atas kebijakan infrastruktur tersebut, sehingga harus dicarikan Solusi sedemikian rupa agar Pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa menimbulkan dampak kerusakan alam maupun lingkungan. Contoh lain, kebijakan pemerintah tentang subsidi pupuk untuk harus bisa dihitung dan dipastikan bahwa kebijakan tersebut mempengaruhi petani dalam peningkatan hasil produksi. Subsidi yang tepat jumlah, tepat jenis dan tepat sasaran akan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Sebaliknya, jika subsidi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan kekecewaan serta membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan sehingga pada akhirnya petani justru dirugikan. Hal lain, misalkan adanya kemudahan import pangan dan pakaian satu sisi bisa mencukupi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih mudah dikendalikan. Akan tetapi bagi petani dan umkm lokal, hal ini bisa menjadi tantangan karena akan menjadi pesaing yang bisa mengancam eksistensi para pelaku industri pangan dan pakaian, terutama mereka yang bergerak di zona usaha mikro dan kecil. Pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan rakyatnya akan mengambil aspirasi dan mendengarkan keinginan rakyatnya. Keputusan yang baik tidak sekedar cukup dengan perencanaan yang baik tapi juga harus melibatkan banyak pihak – terutama rakyat sebagai obyek kebijakan, agar dalam pelaksanaannya rakyat bukan sekedar mendukung tapi secara sadar ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kebijakan tersebut. Jika kembali kepada falsafah jawa “obah ngaraep kobet mburi” maka harus ada kesadaran bersama antara para pemimpin di segala tingkatan dengan rakyat yang dipimpinnya serta semua unsur terkait seperti Partai politik maupun organisasi atau lembaga masyarakat. Pada proses inilah, KPU harus menjadi bagian dari solusi melalui program pendidikan politik terutama kepada masyarakat agar Ketika tahapan pemilihan, masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka dalam pertimbangan pengetahuan dan penuh kesadaran serta masyarakat juga tahu bagaimana mendukung, mensukseskan maupun mengawal program dan kebijakan pemimpin mereka yang terpilih melalui proses pemilu. *Kadiv. Sosdiklihparmas dan SDM KPU Kabupaten Klaten